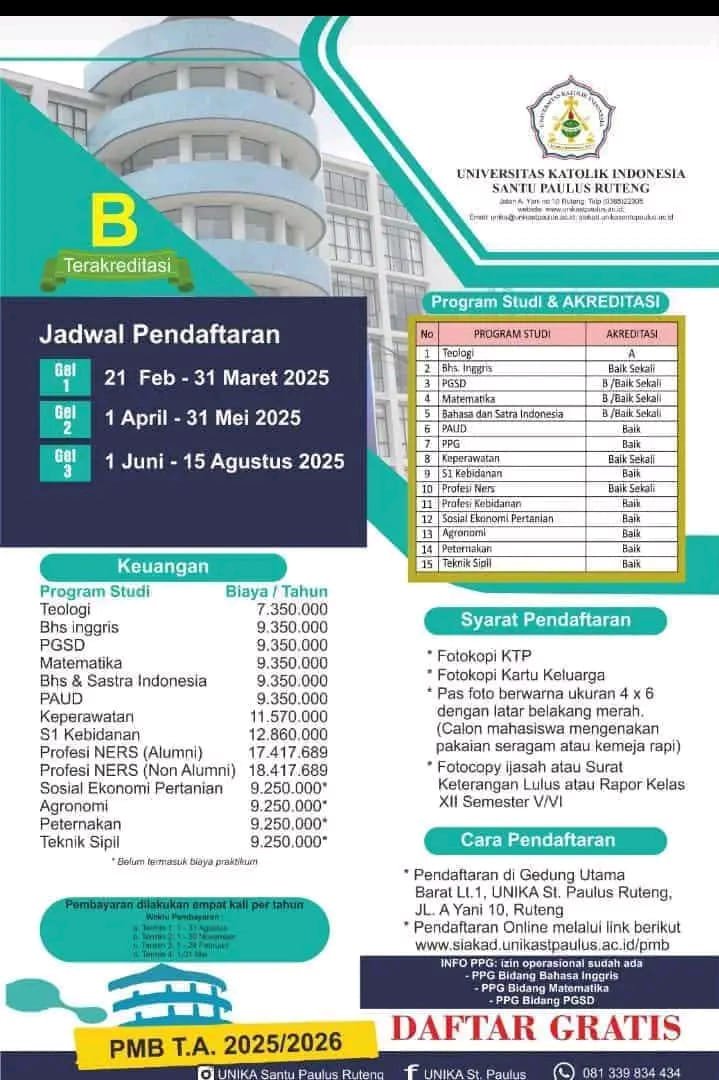Waingapu, Ekorantt.com – Gelombang desakan agar Undang-Undang Kehutanan diubah total datang dari Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam diskusi publik yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTT pada 28 Agustus 2025 di Waingapu, Sumba Timur, masyarakat adat, akademisi, mahasiswa, dan anggota DPRD sepakat bahwa UU Nomor 41 Tahun 1999 sudah tidak lagi relevan dengan tantangan sosial dan ekologis di daerah itu.
Resolusi bertajuk “Suara dari Pulau Sumba: Ubah Total UU Kehutanan dan Segera Sahkan UU Masyarakat Adat” disusun dan dideklarasikan oleh Aliansi Selamatkan Hutan Adat di NTT sebagai bentuk sikap bersama atas kondisi kehutanan di wilayah tersebut.
Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian pra-Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup Indonesia (PNLH) ke-14.
Menurut mereka, UU Kehutanan yang berlaku saat ini telah gagal secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam menjamin kelestarian hutan dan pemenuhan hak masyarakat adat di NTT.
Dalam situasi krisis iklim yang semakin memburuk, kebutuhan akan undang-undang baru dinilai mendesak.
Triawan Umbu Uli Mehakati dari Yayasan Koppesda, organisasi anggota Walhi NTT, mengatakan bahwa pendekatan pengelolaan hutan berbasis pengetahuan adat seharusnya menjadi bagian utama dalam revisi Undang-undang.
“Hal ini sangat mendasar, sehingga tidak bisa hanya revisi beberapa pasal saja, harus ada pengubahan total UU Kehutanan,” kata Triawan.
Ia juga menegaskan pentingnya keberadaan UU Masyarakat Adat agar proses revisi UU Kehutanan memiliki acuan dan keselarasan substansi.
“Jika Undang-undang ini telah disahkan, maka revisi total undang-undang Kehutanan nanti bisa menyinkronkan substansi pengaturannya dengan UU Masyarakat Adat,” lanjutnya.
Pandangan senada disampaikan Umbu Pajaru Lombu, akademisi dari Universitas Kristen Wira Wacana Sumba.
Ia menyoroti penggunaan konsep Hak Menguasai oleh Negara dalam UU Kehutanan saat ini, yang menurutnya berwatak kolonial dan menjadi alat negara untuk menguasai serta merusak hutan.
“Saya harus bilang bahwa negara lah pelaku utama pengerusakan hutan,” tegasnya.
Lombu menyebut, perubahan total UU Kehutanan diperlukan agar pemaknaan Hak Menguasai oleh Negara bisa diluruskan, sebab selama ini pasal tersebut dijadikan tameng dalam berbagai kebijakan yang merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.
Ia mencontohkan proyek konversi 20 juta hektare hutan untuk kebutuhan pangan dan energi sebagai bagian dari perusakan tersebut.
Sementara itu, Umbu Tamu Ridi Djawawara, anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, mengungkapkan kecurigaannya terhadap motif di balik revisi UU Kehutanan di tingkat pusat.
“Sementara kita menginginkan pengubahan menyeluruh UU Kehutanan ini untuk mengakomodir kepentingan rakyat, perlindungan lingkungan, dan melestarikan hutan. Sehingga kita dituntut untuk bisa bersama-sama mengawal proses ini, agar proses revisi menyeluruh dapat dilakukan dan keinginan kita bisa terakomodir,” ujarnya.
Djawawara menekankan pentingnya fungsi hutan sebagai penyenggah ekosistem dan penopang kehidupan masyarakat. UU Kehutanan yang baru diharapkan mampu mengurangi dominasi pemodal dan menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam pengelolaan sumber daya hutan.
Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, memperkuat argumen bahwa UU saat ini gagal secara sosiologis, filosofis, dan yuridis. Ia menilai UU Kehutanan tidak mampu memahami makna hutan bagi masyarakat adat.
“Namun UU Kehutanan dan penyelenggara negara mendefinisikan hutan dalam kacamata teknokratis,” katanya.
Siagian juga menyoroti bahwa proses penetapan kawasan hutan selama ini tidak melibatkan pendekatan etnografi atau pemetaan partisipatif, sehingga kerap menimbulkan konflik tenurial.
“Penetapan kawasan hutan menjadi legal but not legitimate,” ujarnya.
Ia menambahkan, secara yuridis, UU Kehutanan saat ini tidak konsisten dengan putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait definisi hutan dan hak masyarakat adat.
“Secara Yuridis, UU Kehutanan compang-camping secara sistem hukum. Ia tidak mempertimbangkan putusan hasil peninjauan kembali yang Mahkamah Konstitusi keluarkan, seperti definisi hutan dan hak masyarakat. Karena itu, tidak cukup hanya revisi. Butuh UU Kehutanan baru,” tutup Siagian.